Kata “silaturahmi” sudah begitu akrab di telinga kita. Hampir di setiap momen lebaran, reuni, atau acara keluarga, kata ini selalu diulang-ulang seolah sudah jelas maknanya. Kita pun menggunakannya dengan enteng, seperti sekadar sinonim dari kumpul-kumpul, saling sapa, atau jabat tangan. Tapi sebenarnya, apakah silaturahmi sesederhana itu?
Kalau ditarik dari akar katanya, silaturahmi terdiri dari dua unsur: ṣilah yang berarti sambungan atau hubungan, dan raḥim yang berarti rahim, yang secara spesifik merujuk pada ikatan darah. Jadi silaturahmi itu bukan sekadar basa-basi sosial, melainkan menyambung sesuatu yang paling dalam: hubungan asal-usul manusia. Artinya, ketika Nabi ﷺ menekankan pentingnya silaturahmi, yang dimaksud bukan cuma etika sopan santun, tetapi sebuah fondasi keberlangsungan ikatan kemanusiaan. Kira-kira begitu.
Imam al-Nawawī dalam Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud silaturahmi adalah perbuatan baik kepada kerabat sesuai dengan kondisi hubungan yang terjalin antara yang menjalin silaturahmi dan yang menerima silaturahmi. Kadang-kadang dilakukan melalui pemberian materi, kadang melalui bantuan, atau dengan berkunjung, menyapa, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, silaturahmi itu luwes. Ia tidak selalu berbentuk hadiah atau kunjungan, bisa juga dalam bentuk perhatian —dalam bentuk apapun— yang menjaga ikatan yang terjalin antara satu sama lain tetap hidup.
Masalahnya, kebanyakan dari kita memahami silaturahmi sebagai transaksi saja. Kalau dia datang, kita balas datang. Kalau dia memberi, kita balas memberi. Kalau dia menyapa, kita balas menyapa. Ada logika timbal balik yang seolah-olah sudah cukup untuk dijadikan standar. Kita menganggap dengan begitu kita sudah jadi “penyambung silaturahmi.” Padahal, hadis Nabi justru menegaskan sebaliknya, “Bukanlah penyambung silaturahmi itu orang yang sekadar membalas kebaikan, tetapi yang tetap menyambung meski diputus.”
Siapa Penyambung Silaturahmi Itu?
Imam Ibn Ḥajar dalam Fatḥ al-Bārī menurunkan makna hadis ini ke dalam tiga derajat hubungan. Pertama adalah al-wāṣil, orang yang menyambung meski diputus. Ia tidak menunggu, ia memulai. Ia tetap peduli meski diabaikan, tetap datang meski ditolak, tetap memberi meski tidak pernah dibalas. Orang seperti ini jelas melawan logika umum. Karena normalnya, manusia ingin timbal balik. Kalau sudah berkali-kali memberi tapi tidak pernah dihargai, ya wajar saja kalau mundur.
Menjadi al-wāṣil itu artinya rela menaruh harga diri sedikit ke belakang. Rela terlihat “kebanyakan” atau “ngoyo.” Apanya yang kebanyakan dan ngoyo?Ya usahanya untuk menyambung itu. Karena ia sadar, ini bukan soal siapa yang lebih unggul perihal gengsi, tapi soal siapa yang lebih tulus mengusahakan terjaganya sebuah ikatan.
Kedua adalah al-mukāfi’. Inilah yang paling umum. Orang yang hanya membalas sesuai kadarnya saja. Kalau disapa, ia balas menyapa. Kalau tidak, ya sudah. Relasi jenis ini aman-aman saja, tapi rapuh. Kenapa? karena aksinya bergantung pada apa yang dilakukan orang lain kepadanya. Kalau pihak sana berhenti memberi kabar, hubungannya pun ikut ndak ada kabar.
Ketiga adalah al-qāṭi‘, orang yang tidak membalas meski sudah diperlakukan baik. Disapa, tidak menyahut. Diberi, pura-pura tidak tahu. Diingat, malah cuek. Inilah yang disebut dengan memutus silaturahmi. Celakanya, kadang kita sendiri bisa terjebak jadi qāṭiʿ tanpa sadar. Bisa jadi karena gengsi, sakit hati, atau sekedar malas saja.
Jadi, kita ada di level mana sekarang? Jangan-jangan, kita merasa sudah jadi wāṣil, padahal masih berkutat di level mukāfi’. Atau jangan-jangan, kita sudah menjadi seorang qāṭi‘ tanpa disadari?
Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa sabda Nabi diatas adalah sebuah tantangan terhadap mentalitas kita. Kalau hubungan sosial hanya didasarkan pada logika timbal balik, tidak ada bedanya dengan transaksi dagang dong. Padahal, silaturahmi itu seharusnya bisa ditarik ke level yang lebih tinggi, jadi ibadah.
Mungkin saja, hadis-hadis seperti ini merupakan bentuk perhatian Nabi kepada kita. Seakan-akan ada pesan, “kamu bisa kok lebih baik dari biasanya.” Ada ajakan untuk selalu memaksimalkan potensi diri, “versi terbaikmu.” Dalam konteks ini, kita perlu melawan gengsi, rasa malu, dan rasa-rasa lainnya yang bisa mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi.
Karena kita terus berusaha menjadi lebih baik itulah, hidup kita menjadi berkah. Bisa jadi inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi lainnya, yang menyebut bahwa silaturahmi bisa menjadi sebab panjangnya umur, serta luasnya rezeki.
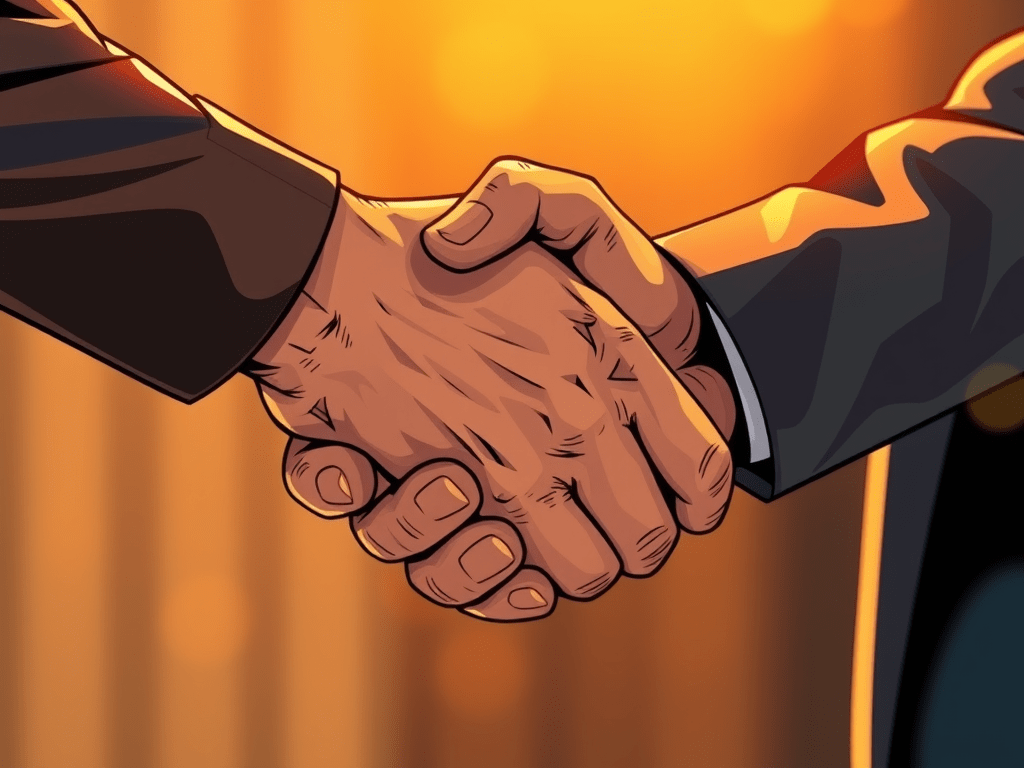
Tinggalkan komentar