Kita mudah terkecoh dengan sesuatu yang tampak seperti pencapaian. Gelar, jabatan, pamor, pengikut, harta, dan yang sejenisnya. Semua itu mudah sekali membuat kita percaya bahwa kita sedang “berhasil.” Padahal, belum tentu demikian. Jangan-jangan, kita hanya sedang melihat fatamorgana di tengah padang pasir saja.
Rasulullah Saw pernah bersabda:
تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ
“Celaka hamba dinar, hamba dirham, dan hamba khamīṣah. Jika diberi, ia senang. Jika tidak diberi, ia murka.”
Dalam Mirqāh al-Mafātīḥ, Mullā ʿAlī al-Qārī menjelaskan bahwa “hamba dinar dan dirham” ini bukan terbatas pada orang yang punya banyak uang saja. Mereka adalah orang-orang yang menaruh hidupnya pada harta, menjadikannya pusat perhatian, mengukurnya sebagai sumber kemuliaan. Begitu pula “hamba khamīṣah”—sehelai pakaian indah yang melambangkan status dan gengsi pada zamannya.
Lalu, kenapa Nabi menyebut dinar, dirham, dan khamīsah? Karena hal-hal ini adalah yang paling berpotensi menghanyutkan. Seseorang bisa jadi merasa “paling” karena punya harta dan status. Ia merasa bisa membayar apapun. Ia merasa lebih tinggi dari siapapun. Makanya, ketika terjebak dalam kondisi seperti ini, ia disebut sebagai budaknya. Kebebasannya telah hilang. Karena setiap keputusan dan perbuatannya akan selalu ditentukan oleh dorongan untuk memperoleh atau mempertahankan semua itu.
Tanda seseorang menjadi hamba dunia bisa dilihat dari perubahan sikapnya. Ketika diberi, ia akan senang. Jika tidak diberi, ia murka. Hidupnya mudah naik turun. Tergantung dengan pemberian, pujian, atau pengakuan. Ciri-ciri ini mirip dengan tanda orang munafik yang digambarkan al-Qur’an: “Apabila diberi bagian dari sedekah, mereka senang. Tetapi jika tidak diberi, mereka marah.” (QS. al-Tawbah: 58)
Inilah ilusi pencapaian yang mungkin sering kita alami. Kita mengira telah “naik kelas” hanya karena mendapatkan sesuatu. Kita menyangka telah menemukan air yang segera akan menghilangkan dahaga, padahal itu hanyalah fatamorgana. Sayangnya, kita tak segera sadar. Setelah tertipu dengan satu fatamorgana, kita menuju fatamorgana berikutnya. Dan begitu seterusnya.
Kita mengira bahwa gelar, jabatan, pamor, pengikut, harta, dan yang sejenisnya itu punya kekuatan. Padahal tidak. Kita terlanjur menempelkan hal-hal semu itu menjadi identitas diri kita. Ketika salah satu hal-hal semu itu dicabut, maka runtuhlah identitas diri kita seluruhnya. Seolah kita telah menjadi budak yang kehilangan tuannya. Bingung, tidak tahu harus berbuat apa lagi.
Sepele sekali diri kita ini. Bahkan, Mullā ʿAlī al-Qārī menyindir, “Jika orang seperti ini terkena duri, maka ia tidak bisa mencabutnya.” Ya kita ini. Ketika diuji dengan kesulitan kecil saja, kita akan mudah terpuruk. Kita benar-benar tidak punya daya untuk bangkit.
Sebenarnya, permasalahannya bukan pada soal kepemilikannya. Tapi perihal keterikatannya. Kita boleh saja memiliki hal-hal semu itu, namun sebaiknya kita tetap sadar bahwa itu semu. Boleh jadi, hari ini nama kita dielu-elukan, ternyata besok sudah dilupakan begitu saja. Hari ini kita diletakkan di atas panggung megah, namun keesokan harinya kita hanya jadi penonton dari belakang panggung. Semua ini mungkin terjadi, dan kita perlu tetap mawas diri. Ojo dumeh!
Kita perlu kembali menghidupkan spirit dari pesan Nabi Saw ini. Jangan sampai kita menjadi “budak pencapaian” yang senang kalau dipuji, marah kalau diabaikan. Karena, persis seperti apa yang disiratkan al-Qārī, hidup semacam itu hanya akan membawa kita pada kekecewaan tanpa ujung. Kalaupun sudah terlanjur, mari kita segera sadar.
Nabi melanjutkan,
طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةً قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ
“Beruntunglah hamba yang memegang tali kudanya di jalan Allah. Rambutnya kusut, kakinya berdebu. Jika ditempatkan di barisan depan, ia ada di sana. Jika ditempatkan di barisan belakang, ia ada di sana.”
Inilah ciri-ciri orang yang terlepas dari perbudakan dunia. Ia tidak menuntut posisi. Mau di depan, ia siap. Mau di belakang, ia juga siap. Tidak ada rasa minder karena tidak terlihat. Tidak ada rasa bangga berlebihan karena disorot. Ia teguh di mana pun ia ditempatkan. Ia sadar dengan peran dan tanggung jawabnya. Inilah orang yang benar-benar merdeka atas dirinya sendiri.
Sosok seperti ini biasanya tidak dikenal di masyarakat. Kalau ia masuk ke sebuah majelis, tidak dihiraukan. Kalau ia memberi usul, tidak diterima. Akan tetapi, meskipun manusia menolaknya, Allah justru mengangkat derajatnya. Ia mungkin tidak punya pencapaian di sisi manusia, tapi ia punya kedekatan dengan Allah yang tidak bisa diukur oleh apapun di dunia.
Namun, sikap seperti ini tidak bisa dibranding. Ia muncul karena kesadarannya sendiri. Para salaf bahkan menyebutkan bahwa ada orang yang sengaja hidup dengan pakaian jelek, seolah-olah ingin terlihat zuhud. Tapi, dalam hatinya, justru ada kesombongan yang lebih besar daripada mereka yang memakai pakaian mewah. Seakan berkata: “Lihatlah kesederhanaanku.” Padahal, itu hanyalah kebanggaan dalam bentuk lain.
Artinya, terjebak dalam ilusi pencapaian tidak hanya terjadi pada orang kaya dan terkenal saja. Bahkan orang yang mengaku zuhud pun bisa terjebak dalam posisi ini, jika hatinya masih terikat dengan penilaian orang lain. Maka, kita perlu belajar untuk merdeka. Jangan mau diperbudak oleh harta dan citra.
Pencapaian sebenarnya adalah ketika kita tetap teguh pada amanah, walaupun tidak ada mata yang tertuju pada kita. Apa amanah itu?
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ
“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.” [QS. Al-Żāriyāt (51): 56]
Tabik,
Ibnu
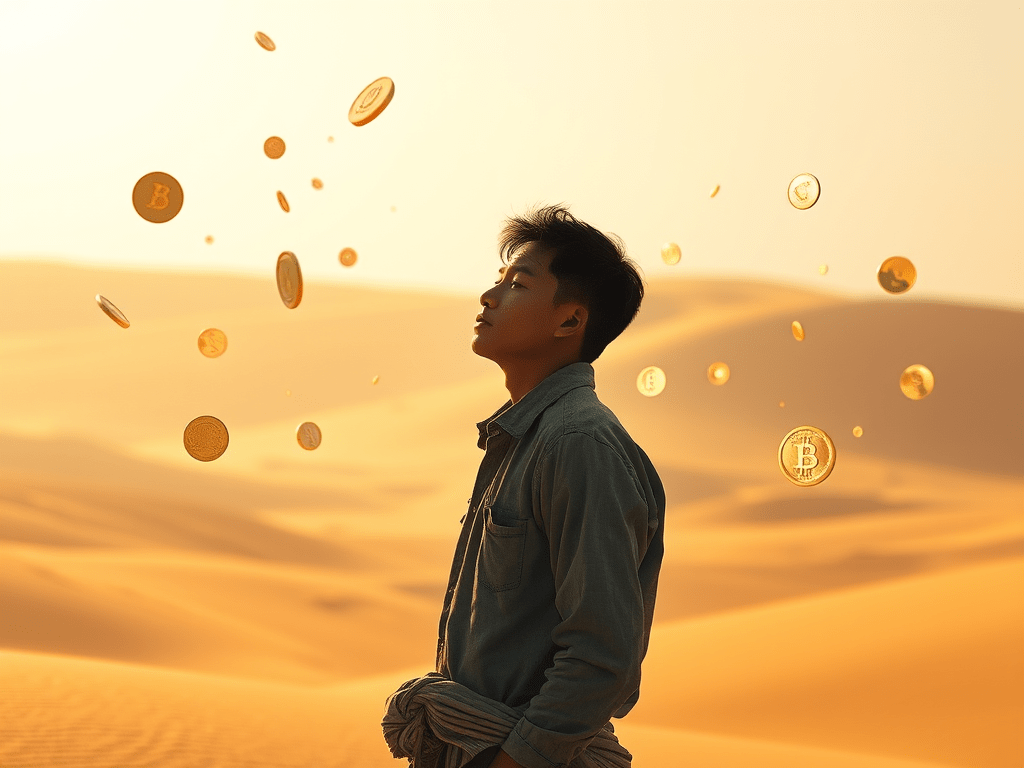
Tinggalkan komentar