Suatu hari, sahabat bertanya kepada Rasulullah ṣallallāhu ‘alayhi wasallam, “Siapa manusia yang paling mulia?” Pertanyaan ini tampak biasa saja, tapi sebenarnya menyimpan kompleksitas. Kata “mulia” bisa bermakna banyak hal. Entah itu mulia di sisi Allah subhānahu wa ta‘ālā, mulia secara keturunan, atau mulia dalam pandangan sosial. Parameter kemuliaan dari semua hal ini berbeda, tidak ada yang sama. Nah, para sahabat awalnya mengajukan pertanyaan ini tanpa memperjelas sudut pandang mana yang mereka maksud, sehingga Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam menjawab dengan mengambil makna yang paling umum dan paling tinggi.
Jawaban pertama Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam tegas dan langsung: “Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.” Ini adalah kemuliaan mutlak, kemuliaan yang tidak terbatas pada ras, suku, atau status sosial —parameternya jelas. Imam al-‘Ainī menjelaskan bahwa jawaban ini mencakup semua jenis manusia tanpa melihat latar belakang mereka. Bahkan jika seseorang adalah seorang budak dari Habasyah, selama ia bertakwa, maka ia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Jawaban ini langsung merujuk pada firman Allah subhānahu wa ta‘ālā dalam surat al-Ḥujurāt: inna akramakum ‘indallāhi atqākum—”Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah subhānahu wa ta‘ālā adalah yang paling bertakwa.”
Ayat ini sendiri turun setelah Allah subhānahu wa ta‘ālā menjelaskan bahwa semua manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, lalu dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal. Pengetahuan tentang nasab dan keturunan memang penting, tapi hanya untuk keperluan praktis, yaitu agar kita tahu siapa yang berhubungan dengan siapa, siapa yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan siapa. Namun ternyata kemuliaan sejati tidak ditentukan oleh garis keturunan. Kemuliaan sejati itu hanya ditentukan oleh ketakwaan, karena akhirat adalah milik orang-orang yang bertakwa, dan yang dilihat Allah subhānahu wa ta‘ālā adalah apa yang ada di dalam hati, bukan apa yang tertulis dalam silsilah keluarga.
Akan tetapi, para sahabat sepertinya belum puas dengan jawaban ini. Mereka menyahut, “Bukan tentang ini yang kami tanyakan.” Rupanya, pertanyaan mereka lebih spesifik dari yang Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam kira. Mereka tidak bertanya tentang kemuliaan mutlak di sisi Allah, melainkan tentang kemuliaan dalam konteks yang lebih sempit, mungkin tentang kemuliaan keturunan atau kehormatan sosial. Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam kemudian menyesuaikan jawabannya. Mungkin beliau berpikir bahwa mereka bertanya tentang kemuliaan yang menggabungkan antara nasab dan akhlak, antara keturunan dan kualitas pribadi.
Maka Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam menjawab lagi, “Kalau begitu, yang paling mulia adalah Yusuf ‘alayhissalām, seorang nabi putra nabi, putra nabi, putra Khalilullah .” Memang benar, nabi Yusuf ‘alayhissalām adalah putra nabi Ya’qub ‘alayhissalām, cucu dari nabi Ishaq ‘alayhissalām, dan cicit nabi Ibrahim ‘alayhissalām. Garis keturunannya dipenuhi dengan nama para nabi mulia, dan nabi Ibrahim ‘alayhissalām sendiri digelari khalīlullāh, kekasih Allah subhānahu wa ta‘ālā.
Belum cukup sampai di situ, nabi Yusuf ‘alayhissalām juga memiliki kemuliaan pribadi yang luar biasa. Beliau adalah seorang nabi yang diberi ilmu tentang takwil mimpi, pemimpin yang bijaksana dan adil, memiliki paras rupawan, dan tentu saja termasuk seorang yang menjalani kehidupan penuh ujian dengan kesabaran yang sempurna. Semua unsur kemuliaan—nasab, ilmu, kepemimpinan, kesabaran, dan keindahan—terkumpul dalam diri Yusuf ‘alayhissalām. Inilah sebabnya Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam menyebutnya sebagai orang yang paling mulia, jika yang dimaksud adalah kemuliaan yang menggabungkan antara keturunan dan kualitas personal.
Namun rupanya para sahabat belum cukup puas dengan jawaban itu. Mereka menyahut lagi, “Bukan tentang ini juga yang kami tanyakan.” Barulah saat itu Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam bertanya dengan lebih rinci, “Apakah kalian bertanya tentang kemuliaan suku-suku Arab?” Mereka menjawab, “Ya.” Pertanyaan mereka ternyata sangat spesifik, ada rasa ingin tahu tentang nasab bangsa Arab, suku-suku, dan kabilah-kabilah mereka, siapa yang lebih mulia dan siapa yang kurang mulia dalam konteks keturunan.
Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam lalu bersabda, “Orang-orang terbaik di kalian pada masa jahiliyah adalah yang terbaik pula di masa Islam, jika mereka memahami agama.” Ini adalah jawaban yang sangat bijaksana. Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam tidak serta-merta menafikan kehormatan keturunan, tidak mengatakan bahwa semua orang Arab sama saja tanpa perbedaan. Beliau mengakui bahwa ada suku-suku yang memang memiliki kemuliaan sosial di masa jahiliyah, yang dikenal karena kedermawanan mereka, keberanian mereka, atau kebijaksanaan mereka. Namun, kemuliaan itu hanya akan bertahan di masa Islam jika disertai dengan satu syarat yang sangat penting: iżā faqihū—jika mereka memahami agama.
Kata faqihū di sini bukan hanya soal hafal hukum-hukum fiqih atau tahu dalil-dalil syariat. Imam al-‘Ainī menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fiqh adalah pemahaman yang mendalam tentang adab-adab syariat dan hukum-hukum Islam, yang kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah ilmu yang tidak hanya berhenti di kepala, ia turun ke hati dan menggerakkan anggota badan. Buahnya adalah amal salih, sehingga fiqh dalam makna ini identik dengan takwa. Seseorang yang benar-benar memahami agama akan bertakwa, dan seseorang yang bertakwa pasti memiliki pemahaman yang benar tentang agama. Keduanya tidak bisa dipisahkan.
Dengan syarat ini, tampaklah bahwa tidak semua orang yang berasal dari keturunan mulia di masa jahiliyah akan tetap mulia di masa Islam. Bagaimana tidak? Ternyata ada yang masuk Islam tapi hatinya masih terikat pada nilai-nilai jahiliyah, ada juga yang memeluk Islam hanya karena ikut-ikutan tanpa benar-benar memahami esensi ajaran agama ini, pun ada yang masuk Islam tapi niatnya hanya untuk mengeruk kepentingan duniawi. Orang-orang seperti ini, meskipun memiliki nasab yang terhormat, tidak akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah subhānahu wa ta‘ālā. Sebaliknya, orang yang benar-benar memahami Islam dan mengamalkannya, meskipun berasal dari keturunan yang tidak bagus-bagus amat, akan mendapatkan kemuliaan yang jauh lebih tinggi.
Tentu keturunan bisa menjadi modal awal, tapi yang namanya modal itu harus dikelola dengan baik. Seandainya tidak dikelola dengan ilmu dan ketakwaan, modal itu akan hilang. Kita bisa mengandaikannya seperti orang yang mewarisi banyak harta, tapi tidak tahu cara mengelolanya, lama-kelamaan hartanya akan habis tak bersisa sedikit pun. Begitu pula dengan kemuliaan keturunan yang apabila tidak dijaga dengan amal saleh, kemuliaannya akan lenyap.
Sabda ini mengantarkan kita untuk kembali pada ayat inna akramakum ‘indallāhi atqākum. Semua penjelasan tentang kemuliaan keturunan, pada akhirnya, tetap bermuara pada ketakwaan. Namun, sebagaimana Allah subhānahu wa ta‘ālā berfirman dalam QS. Al-Najm, falā tuzakkū anfusakum huwa a’lamu bi man ittaqā—”Janganlah kamu mensucikan dirimu sendiri, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa.” Kita tidak bisa mengklaim bahwa kita lebih bertakwa dari orang lain. Hanya Allah subhānahu wa ta‘ālā yang tahu isi hati kita yang sebenarnya. Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam sendiri pernah mengisyaratkan hal ini dengan menunjuk dadanya dan berkata, “Takwa itu di sini,” seakan-akan mengatakan bahwa ketakwaan yang sebenarnya hanya ada di dalam hati, dan hanya Allah subhānahu wa ta‘ālā saja lah yang bisa melihatnya.
Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sabda Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam ini? Pertama, kita perlu berhati-hati dalam mengukur kemuliaan. Jangan sampai kita terjebak dalam pandangan yang sempit, yang hanya mempertimbangkan aspek keturunan, harta, atau jabatan sebagai parameter kemuliaan. Kemuliaan yang sebenarnya adalah takwa, dan takwa itu tersembunyi di dalam hati. Kedua, kita perlu menghargai ilmu dan pemahaman agama. Tanpa pemahaman yang benar, semua modal yang kita miliki—baik itu keturunan, harta, atau kedudukan—tidak akan ada artinya. Ketiga, kita perlu menjaga diri dari sikap ‘aṣabiyyah, yaitu fanatisme buta terhadap suku atau kelompok. Nabi ṣallallāhu ‘alayhi wasallam pernah bersabda, “Bukan dari golongan kami orang yang menyeru kepada fanatisme kesukuan, atau yang berperang karena fanatisme kesukuan.” Fanatisme semacam ini adalah warisan jahiliyah yang harus kita tinggalkan.
Kita boleh saja bangga dengan keluarga kita, dengan suku kita, dengan komunitas kita. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi kebanggaan itu tidak boleh membuat kita membangga-banggakan diri sampai meremehkan orang lain, atau merasa lebih baik dari komunitas atau kelompok lainnya. Kemuliaan yang sejati tidak diwariskan begitu saja, namun harus diraih dengan usaha, ilmu, dan takwa. Dan yang terpenting, hanya Allah subhānahu wa ta‘ālā lah yang bisa menilai kemuliaan sejati itu. Tugas kita hanya berusaha menjadi hamba yang baik, yang terus belajar, yang terus beramal, dan terus memperbaiki diri. Sisanya, kita serahkan pada Allah subhānahu wa ta‘ālā.
Tabik,
Ibnu
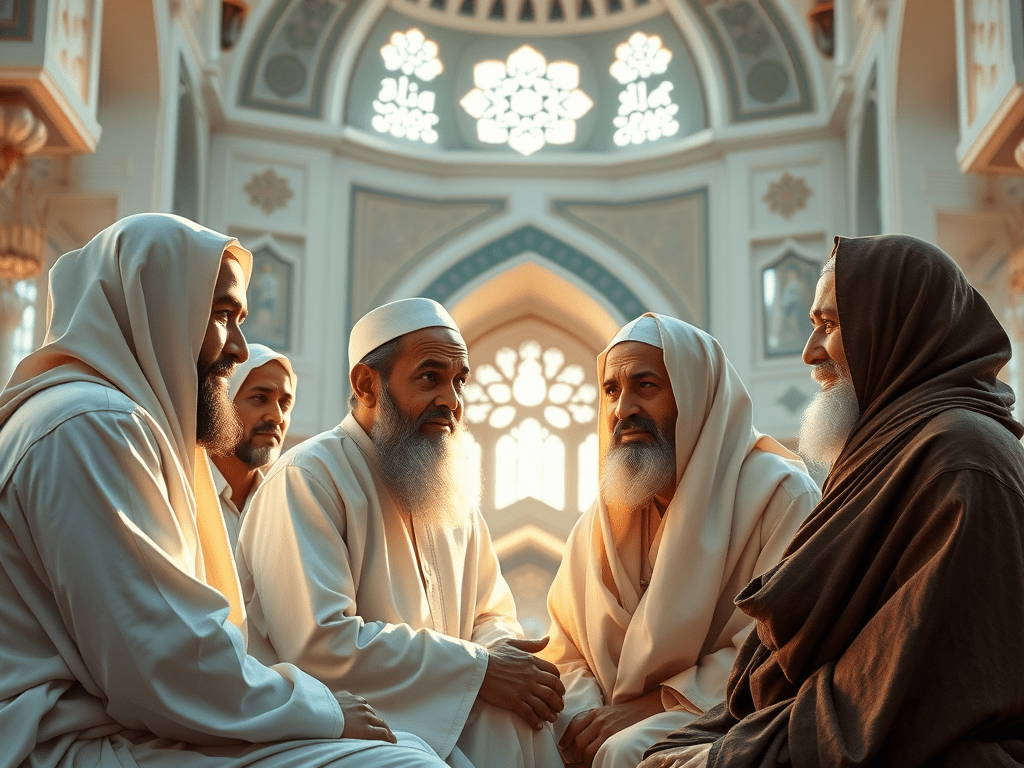
Tinggalkan komentar