Imam al-Muzanī, salah satu murid jagoan Imam al-Syāfi’ī, pernah berkata, “Aku membaca kitab al-Risālah karya Imam al-Syāfi’ī sebanyak 500 kali. Setiap kali membacanya, aku selalu menemukan faidah baru yang tidak kudapatkan pada bacaan sebelumnya.”
Lima ratus kali lho. Bukan satu-dua kali. Bukan sepuluh atau dua puluh kali. Lima ratus kali membaca kitab yang sama, dan tetap menemukan sesuatu yang baru. Kok bisa?
Bukankah seharusnya, setelah membaca berkali-kali, kita semakin hafal isinya? Bahkan mungkin tidak ada yang tersisa untuk dipelajari lagi? Ternyata tidak. Ilmu itu berlapis. Ada yang kadang hanya tampak di permukaan, ada yang lebih tersembunyi lagi di kedalaman. Nah, untuk sampai ke lapisan yang lebih dalam, diperlukan sesuatu yang lebih dari sekadar membaca (atau mendengarkan).
Imam al-Muzanī tentu bukan orang biasa dan sepertinya, beliau juga bukan pembaca pasif yang hanya pengen “selesai.” Beliau membaca dengan kerendahan hati, pikiran yang terbuka, dan niat yang terus diperbaharui. Setiap kali membuka al-Risālah, beliau datang dengan kondisi batin yang berbeda. Mungkin pada bacaan yang ke-50, beliau sedang menghadapi masalah fikih tertentu. Pada bacaan ke-200, mungkin beliau sudah lebih matang dalam memahami ushūl. Dan pada bacaan ke-400, mungkin pengalaman hidup beliau sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Sehingga, teks yang sama bisa berbicara dengan cara yang berbeda.
Inilah yang dimaksud dengan kerendahan hati dalam menuntut ilmu. Ketika seseorang merasa sudah tahu, pintu ilmu akan tertutup baginya. Sebaliknya, ketika ia sadar bahwa dirinya masih bodoh, pintu itu akan terbuka lebar. Syaikh al-Zarnūjī, dalam Ta‘līm al-Muta‘allim, menyebutkan bahwa:
“Dan selayaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk mendengarkan ilmu dan hikmah dengan penuh penghormatan dan rasa hormat, sekalipun ia mendengarnya hanya satu masalah atau satu hikmah sebanyak seribu kali.“
Beliau juga mengutip sebuah ungkapan untuk mempertegasnya, “barang siapa yang penghormatannya setelah seribu kali tidak sama seperti penghormatannya pada kali pertama, maka ia bukanlah termasuk ahli ilmu.“
Menghormati ilmu inilah yang menjadi salah satu aspek terpenting dalam menuntut ilmu. Jika kondisi batin kita mengabaikan sikap penghormatan itu, maka ya pantas saja kalau ilmu hanya akan berakhir masuk kuping kiri, lalu keluar kuping kanan. Hanya lewat, mampir saja tidak.
Makanya, Imam al-Ghazālī juga mengatakan dalam Iḥyā’ bahwa salah satu adab penuntut ilmu adalah lebih fokus pada ilmu batin, menjaga hati, dan menempuh jalan menuju akhirat dengan sungguh-sungguh. Sebab, mujāhadah (kesungguhan dalam berjuang melawan hawa nafsu) akan mengantarkan pada musyāhadah (penyaksian hakikat). Rahasia-rahasia ilmu akan terbuka melalui perjuangan batin, bukan hanya melalui buku dan pengajaran.
Kalau pendekatan ini di-skip, maka jangan heran bila ada orang yang belajar bertahun-tahun, tapi ilmunya tidak pernah melampaui apa yang ia dengar. Sebaliknya, ada orang yang cukup belajar pada hal-hal penting, namun karena fokus pada amal dan menjaga hatinya, Allah membuka baginya hikmah-hikmah yang mengagumkan.
Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abū Nu‘aym al-Asbihānī, disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Barangsiapa mengamalkan ilmu yang ia ketahui, Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui.“
Inilah kunci berikutnya, mengamalkan ilmu. Ilmu yang tidak diamalkan laksana ilmu yang mati. Ia hanya menumpuk di kepala tanpa pernah sampai ke hati, apalagi ke tindakan. Sedangkan ilmu yang diamalkan akan terus berkembang, memperdalam pemahaman, dan membuka pintu-pintu ilmu baru yang sebelumnya tertutup.
Kita akan banyak menemukan ungkapan ulama yang mendorong seseorang untuk mengamalkan ilmunya. Bahkan, tidak jarang mereka “mengancam” orang-orang yang punya ilmu, tapi tidak mau mengamalkannya. Dalam term Jawa, orang-orang seperti ini biasa disebut dengan “omong thok” atau “jarkoni,” alias iso ujar, tapi ora iso ngelakoni —bisa mengucapkan, tapi tidak bisa mengamalkan.
Dalam al-Qur’an sendiri, ada ayat yang khusus menyinggung tentang jarkoni ini. Allah Swt berfirman:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ
“Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan.” (QS. Aṣ-Ṣaff [61]:2-3)
Syaikh al-Ṭanṭawī menyebutkan bahwa apabila sesuatu telah disebut amat besar kemurkaannya di sisi Allah, berarti kemurkaan itu telah mencapai puncaknya. Sehingga tidak ada lagi keraguan tentang besarnya celaan dan beratnya dosa tersebut. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Allah telah mencela dengan sangat keras orang-orang yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan.
Bukan hanya jarkoni itu saja, Syaikh al-Ṭanṭawī juga menuturkan bahwa celaan dan kecaman ini meliputi: sikap senang dipuji dan disanjung tanpa melakukan amal yang pantas untuk dipuji, dusta dalam ucapan, serta ingkar terhadap janji.
Imam al-Ghazali sendiri, dalam kitab kecilnya yang berjudul Ayyuhā al-Walad (Khulāṣah al-Taṣānīf al-Taṣawwuf), sangat menekankan pentingnya mengamalkan ilmu, sekaligus beramal dengan ilmu. Sampai-sampai beliau berkata, “ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu tidak ada nilainya.”
Maka, ketika Imam al-Muzanī membaca al-Risālah untuk kesekian kalinya, beliau bukan hanya membaca teks. Beliau membaca dengan bekal pengalaman mengamalkan apa yang sudah dibaca sebelumnya. Sehingga, setiap bacaannya menjadi lebih kaya dan lebih dalam.
Kita mungkin tidak akan membaca satu kitab sebanyak 500 kali. Tapi kita bisa belajar dari sikap Imam al-Muzanī yang tidak cepat merasa tahu. Beliau tidak bosan dengan teks yang sudah dibaca berulang-ulang. Ilmu itu hidup, dan ia terus bergerak, terus membuka diri, terus menawarkan makna baru—asalkan kita datang dengan kerendahan hati.
Begitu pula dengan al-Qur’an. Berapa kali kita membaca ayat yang sama, tapi baru kali ini kita merasa tertampar olehnya? Berapa kali kita mendengar nasihat yang sama, tapi baru sekarang kita benar-benar memahaminya? Itu semua karena kondisi batin kita berbeda. Pengalaman hidup kita berbeda. Dan yang paling penting, amal kita berbeda.
Kalau begitu, apa yang perlu kita lakukan? Pertama, baca dengan niat yang tulus. Kedua, amalkan apa yang sudah dibaca. Ketiga, baca lagi dengan hati yang lebih rendah. Dan seterusnya. Siklus ini tidak akan pernah selesai, karena luasnya ilmu ibarat samudera yang tidak akan pernah bisa kita jelajahi seluruhnya.
Allāhu a‘lam
Tabik,
Ibnu
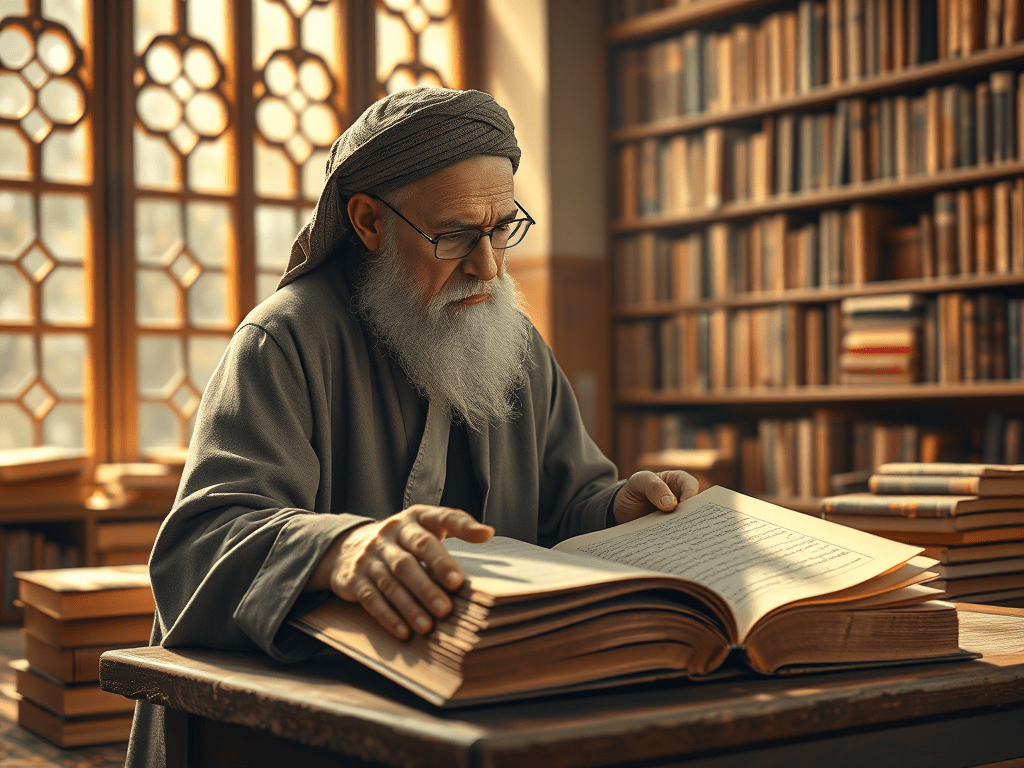
Tinggalkan komentar